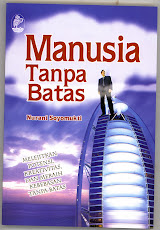Maka demikianlah, turun naiknya kesadaran itu berlangsung begitu panjang: dari berkesadaran maju, dipukul lalu menurun, ada kontradiksi dan pemicu maju lagi, dst.
Dan kita melihat setelah reformasi berjalan hampir satu dekade, kesadaran mahasiswa seakan menurun: disorientasi, demoralisasi, tercerai-berai, dan lain-lain sebagainya. Bahkan, mahasiswa dipandang buruk karena tingkah laku dan gaya hidupnya yang liberal, dianggap tak bermartabat. Tetapi apakah hanya karena itulah lantas kita apatis terhadap mahasiswa?
Saya percaya pada moral dan etika. Tetapi memandang gaya hidup dekaden mahasiswa di era neoliberal sekarang ini sebagai keadaan yang hadir begitu saja (tanpa sebab-sebab material) merupakan kebodohan. Saya mungkin menjadi mahasiswa pada suatu masa di mana kebudayaan yang berkembang tidak seburuk sekarang dalam memundurkan dan mendegenerasikan pola pikir dan tindakan kaum muda. Saya pernah bangga menjadi aktivis mahasiswa di era pasca-1998, dan pernah bangga dengan heroisme perlawanan kaum muda, dan sempat berbangga diri hanya karena pernah menjadi buron pemerintah karena ikut ‘aksi bakar-bakaran’ menjelang pemilu 2004—belakangan saya sadari bahwa itu hanyalah sejenis heroisme kacangan.
Tapi kesombongan dan heroisme memang sejenis ‘opium’ yang di satu sisi mirip penyakit yang menjangkiti gerakan mahasiswa-rakyat, tetapi kadang juga dibutuhkan untuk menyemangati para “rebellious spirit” di kalangan kaum muda. Dan, sayang sekali, kini semuanya hilang. Heroisme yang dulu menjangkiti mahasiswa, yang memang dibutuhkan untuk mengestetisasi sejarah perlawanan, kini musnah.
Romantisme memang ada, tetapi yang diadopsi kalangan mahasiswa saat ini adalah romantisme kacangan. Romantisme yang ditiupkan oleh nafas modal, dan dihirup oleh anak-anak yang seharusnya belajar berhitung atau menyapa realitas dunianya sehingga mengetahui apa yang terjadi dan tidak terasing dari dunianya. Sebab manusia yang terasing dari dunianya adalah sejenis manusia yang tidak memahami arti hidup. Dan, meskipun mengaku memahami keindahan dan romantisme, mereka sama sekali tidak menjuampai keindahan. Karena—sebagaimana dikatakan Chernysevsky—keindahan sejati adalah kehidupan: “Tidak ada yang lebih indah dari pada kehidupan itu sendiri”. Keindahan kehidupan tak dapat direduksi dengan lukisan, puisi, atau khayalan. Kontradiksi dalam kehidupan material adalah keburukan, jeleknya kenyataan, yang juga membuat berpikir timpang. Kenyataan harus diselami sebab—tidak seperti yang dilantunkan oleh lagu-lagu kacangan—hidup bukanlah sandiwara. Para penindas tidaklah bersandiwara atau berpura-pura, orang yang terindas juga serius dalam merasakan pedihnya kesengsaraan dalam hidup. Mungkin mereka yang tertindas hanya tertawa menghibur diri atau lari ke kekosongan reliji, tapi ada sebagian yang tetap tak bisa menyembunyikan perasaannya yang marah akibat penindasan itu.
Dan kehidupan sejati, realitas, kenyataan, tidak pernah dapat dipahami karena mahasiswa sekarang tak lagi belajar, membaca, dan aksi atau mengintegrasikan diri dengan realitas. Mereka memenjarakan diri ke menara gading: kekuasaan yang berdiri di atas penindasan terhadap rakyat, ditopang oleh suatu desain budaya di mana kaum muda diciptakan hanya untuk membeli dan mengkonsumsi atau bergaya seperti kaum borjuis yang tidak pernah melakukan apa-apa demi kemanusiaan, menindas dan menutup-nutupi keburukannya dengan kedermawanan semu dan ritualitas gaya hidup yang mampu melenakan kaum muda untuk berpikir tentang kenyataan sebenarnya. Hedonisme, paham mengejar kesenangan hidup pada saat kontradiksi menganga bagai luka dalam tubuh kehidupan. Hedonisme menutup mata hati dan pikiran mereka akan ‘kasunyatan’. Selama ini mahasiswa hanya dijauhkan dari kenyataan bagaimana rakyat menderita, dikurung dalam kampus, diracuni dengan kesenangan semu. Yang dilihat hanyalah kesenangan dan kepuasan diri. Pada hal, sebagaimana ditegaskan Pramoedya Ananta Toer yang berkata melalui mulut Nyai Ontosoroh dalam novel ‘Bumi Manusia” (hal. 120): "Cerita tentang kesenangan selalu tidak menarik. Itu bukan cerita tentang manusia dan kehidupannya, tapi tentang surga, dan jelas tidak terjadi di atas bumi kita ini”.
Sekarang kita telah kehilangan parameter kemanusiaan. Apa yang disebut sebagai mahasiswa adalah mereka yang belajar di kampus, tapi dusta-dusta sejarahnya sebagai bagian dari kehidupan sangat jelas di depan mata. Kekuatan pembebasan telah hilang, bahkan sedikit sekali, tercerai-berai dan terhalang dengan tembok kekuasaan modal yang dapat beranak-pinak menjadi kebudayaan yang memang menghalangi mahasiswa menuju hakekat sejatinya dalam sejarah: kaum intelektual, agregat perubahan, maupun agen of social control—atau lebih maju lagi menjadi kekuatan revolusioner dalam mosi historis sejarah dalam pertentangan kelas antara kaum tertindas dan penindas.
Bermacam-macam yang dapat kita jumpai dan rata-rata tak jelas jluntrungannya dari aktivitas mahasiswa sekarang ini. Mereka memang rajin datang ke kampus, tandatangan absensi, mendengarkan kuliah, kebanyakan hanya mendengarkan tanpa pertanyaan atau memberikan argumen segar. Lalu mereka berkumpul di kantin atau di tempat-tempat duduk yang indah di kampus... Apa yang mereka bicarakan? Merk produk terbarukah? Tukar pengalaman “dugem-dugeman” atau teman kencan (“pacar”) kah? Adakah banyak waktu yang digunakan untuk membaca, berdiskusi, rapat untuk menyusun aksi penyadaran dan tuntutan mendesak dan strategis untuk melawan ketidakadilan dalam kehidupannya?
Barangkali kita sudah tahu sama tahu (“te-es-te”) bagaimana wajah kampus kita dan apa aktivitas mahasiswa sekarang. Bahkan menjalani aktivitas akademis secara konsisten saja tak pecus. Pikiran mereka belepotan, kemalasan meraja, dan hidupnya dipenuhi absurditas. Tanpa penjelasan. Terombang-ambing oleh prasangka-prasangka kekanak-kanakan yang (sengaja) dibikin oleh kekuatan modal.
Dan Soe Hok Gie pernah mencatat: “Saya membayangkan seorang mahasiswa antropologi, yang berusia sembilan belas tahun datang dengan cita-cita untuk membuat field work di pedalaman Kalimantan atau Irian Barat. Atau seorang mahasiswa jurusan kimia yang berfikir untuk menemukan sejenis cairan baru yang dapat melambungkan manusia ke bulan. Atau seorang mahasiswa hukum dengan ide-ide yang sarat dengan rule of law. Tidak ada yang lebih kejam dari pada mematahkan tunas-tunas semangat kemerdekaan berfikir dan berkreatifitas. Dalam waktu beberapa tahun, pemuda berumur sembilan belas tahun ini mengetahui tak mungkin ada ‘field work’ ke Irian Barat atau pedalaman Kalimantan. Ia harus puas dengan skripsi tentang masyarakat tukang buah-buahan di Pasar minggu. Dan alumnus Kimia benar-benar menyadari yang ada untuknya hanyalah kerja di pabrik sabun atau mentega. Pelan-pelan ia harus melupakan idealismenya tentang cairan yang dapat melontarkan manusia ke bulan. Lalu, si mahasiswa fakultas hukum mengetahui, bahwa di atas hukum terdapat hukum yang tidak tertulis. Tentara, polisi, jaksa dan garong-garong yang punya koneksi”.
Maka demikianlah, yang ingin dikatakan Gie adalah bahwa, ia hanya membayangkan keberadaan mahasiswa yang ideal. Tetapi dalam kenyataan Gie hanya melihat pragmatisme dan oportunisme, juga hedonisme. Watak yang menonjol itu bukannya tanpa sebab, tetapi karena kekuasaan yang dijaga oleh aparat. Pragmatisme bersifat sistemik dan merupakan bagian dari kerja kapitalisme neoliberal yang membuat mahasiswa menjadi pragmatis. Jadi, saya adalah agregat kecil dari kehidupan (bagian dari alam maha luas) yang masih percaya bahwa mahasiswa Indonesia masih punya potensi untuk bangkit. Ingat bahwa sejarah berjalan secara dialektis. Kontradiksi yang terjadi itu sendiri pada dasarnya adalah landasan dari perubahan.
Jadi kemunduran kesadaran mahasiswa—yang tercermin dari gaya hidup mahasiswa, watak, dan tindakannya—sekarang ini adalah bagian dari epos sejarah yang tetap akan bisa berubah. Serangan ideologi neoliberalisme memang semakin masif, tetapi pada saat yang sama krisis yang ditimbulkannya cukup parah. Pada saat mahasiswa terkurung dalam budaya bisu, sekarang ini rakyat justru melawan di mana-mana dengan berbagai macam tindakan dan perspektif atau ekspresinya. Buruh, tani, kaum miskin perkotaan lebih radikal dalam tindakannya.
Seiring dengan epos krisis kapitalisme yang terus berjalan, dan kesadaran berlawan juga pasti akan menular meluaskan perlawanan di sektor rakyat, mahasiswa masih punya potensi untuk bangkit. Kita akan melihat peran mereka yang sesuai dengan sejarahnya. Kita akan mendengar mereka berkata dan membatin, sebagaimana dipikirkan oleh Minke dalam novel “Bumi Manusia” karya Pram (hal. 135): “Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji, dan kecurangan. Duniaku bumi manusia dengan persoalannya”. Masih ada potensi bagi mahasiswa untuk menjalani kuliah bukan demi tujuan yang remeh-temeh, tetapi demi persoalan kemanusiaan (yang ingin dipecahkannya). Sekarang memang masih ada, meskipun kecil. Tetapi saya yakin, juga akan semakin bertambah kelak.
***
Ide penulisan dan penyusunan kata-kata yang kemudian menjadi buku ini murni datang dari diri saya sendiri karena awalnya hanya berupa catatan-catatan sentimentil yang saya lakukan sejak saya menjadi mahasiswa di sebuah kampus negeri di Jember (Jawa Timur), kampus kecil yang dibilang tidak cukup terkenal tetapi sempat mewarnai gerakan mahasiswa di era pasca-reformasi.
Tak mengherankan jika ucapan terimakasih yang terutama saya ucapkan pada kawan-kawan Jember yang bersama penulis, mulai tahun 2002 hingga tahun 2005, sempat meradikalisir gerakan mahasiswa. Kita rasakan bagaimana sulitnya mengorganisir gerakan, juga (harus jujur) termasuk mengorganisir diri-sendiri di tengah godaan-godaan pragmatisme dan oportunisme di tengah masyarakat kapitalis—yang membuat kita bersitegang karena terjadi pertarungan antara keinginan kita untuk melihat rakyat melawan di mana-mana dengan keinginan kita untuk mewujudkan obsesi-obsesi individu (yang saya kira berkaitan dengan dorongan alamiah dalam tubuh kita).
Tidak sedikit kawan-kawan itu yang mengorbankan banyak hal, tuntutan (dan bahkan tekanan orangtua), pacar/istri, birokrasi kampus, hanya untuk melawan budaya bisu (“anti-perlawanan”). Dan untuk menghormati merekalah, tesis yang saya angkat dalam buku ini adalah pentingnya meletakkan kepedulian universal—Cinta universal ala Gibranian, Marxian, dan bukan cinta di kalangan mahasiswa yang hanya berujung pada aktivitas kehidupan yang biasa (kuliah, bersenang-senang, kerja [atau terpaksa menganggur karena keadaan], beranak-pinak atau bersenang-senang dengan kelamin, lalu kehidupan sudah habis di situ tanpa warisan apa-apa pada sejarah)!
Mereka yang menghiasi jiwanya dengan keberanian, dan kadang masuk terlalu jauh dalam menghadapi resiko terhadap nasib eksistensi individual, adalah agregat-agregat sejarah. Mungkin kalian banyak dicemooh dan dianggap tak berguna oleh mereka yang memandang segala sesuatu secara biasa dan temeh. Tapi aku yakin, sejarah memberi hormat pada kalian, sejarah adalah realitas kehidupan yang diam dalam bahasanya sendiri menunggu perubahan yang didorong oleh bagian-bagian darinya—kitalah bagian yang penting itu karena kita berpikir dan bertindak berani, berbeda, dan tidak mengikuti kesepakatan kumpulan binatang gembala yang kemudikan oleh kepentingan kapitalis yang menguasai cambuk dan tongkat untuk menghela kambing-kambing yang bodoh itu. Kepada Ahmad Zaennurrofik, Fajar Dwinanto Harimurti, Heppy Nurwidyamoko, Abdul Basid, Amik Pasaribu, Wawan, dll—kalian pernah mengecat tembok sejarah, memulai pada epos itu!
Ucapan terimakasih juga seharusnya saya haturkan pada beberapa kawan di Yayasan Komunitas Teman Katakata (KOTEKA) yang sekaligus penulis-penulis muda berbakat (Eri Irawan, Maya Siandhira, Deny Ardyansah, Agustinus Suprapto, Timo Teweng, Beta Candra Wisdata, Berti); sepasang intelektual muda Lukman Hakim dan Mbak Indah di The Academos Society (TAS) Pasca-sarjana UNEJ; Edy Firmansyah dan Pram Kecil di Sanggar Bermain Kata (Madura); Mbak Ajeng YAPPIKA Jakarta yang membantu proses pengeprinan naskah; Mas Abubakar Ebi Hara, Phd, Mr. Sugiyanto, Pak Supriyadi, dan akademisi yang berpikiran ilmiah dan maju lainnya di almamater penulis. Kawan-kawan di garis rakyat memberikan banyak warna dan ruang dalam penyelesaian karya ini; kawan-kawan di JAMAN (Jaringan Kaum Muda untuk Kemandirian Nasional), ada Iwan Dwi Laksono, Gigih Guntoro, Paul, Kaka, Dedi, dll; Seluruh elemen gerakan mahasiswa yang ada (HMI, IMM, PMII, GMNI, GMNI KS, FMN, HIKMAHBUDI, PMKRI, HMI-MPO, KAMMI, IPPNU, IPNU, SMI, BM PAN, JMD, KMHDI, KIPAS, SRMK, STN, dll); kawan-kawan jurnalis muda di Tegalboto, Ecspose, dll.
Yang tak terlupakan, ucapan terimakasih juga saya haturkan pada Mbak Tie, Ibu Siti Fatonah dan keluarga (Nabila, Rizal Fikri, Etika, Deni, Amin Tohari, Mariam, Masroji, dll)—kalianlah yang banyak memberikan doa dan dukungan atas semua kegitanku; juga calon anak-anakku kelak (Tinta Realista Chavista, Hugo Karna Pramodya, dll); juga “keluarga di Jember” (Ibunda Denok dan Bapak Milko dan Adik Adin/Zinedin Stinjte Harimurti)—mereka semua secara langsung atau tidak (secara psiko-spiritual) terlibat dalam proses menyelesaikan naskah ini. Juga Bung Daniel Hikmahbudi dan Mas Angga (Erlangga Pribadi) yang memberikan pengantar dan sekaligus mengapresiasi karya dalam buku ini. Yang paling pivotal adalah penerbit Arruzzwacana (Mas Masrur) Yogyakarta yang bersedia mengambil keberanian untuk menerbitkan karya ini.
Akhir kata, tiada gading yang tak retak, kesempurnaan bukan milik manusia dan proses pembuatan karya ini. Masih ada celah-celah dan kekurangan baik secara substansi maupun teknis di dalamnya. Selayaknyalah penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.
Jakarta-Jember, Oktober 2007
Nurani Soyomukti
[1] Max Lane. Bangsa Yang Belum Selsai: Indonesia Sebelum dan Sesudah Soeharto. Jakarta: Reform Institute, 2007
[2] Prisma, 20 Maret 1973, hal. 32
[3] Lihat Arbi Sanit, “Gerakan Mahasiswa 1970-1973: Pecahnya Bulan Madu Politik”, dalam Muridan S. Widjojo (ed.), Penakhluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa ’98. Jakarta: Sinar Harapan, 1999, hal. 46
[4] Tuntutan agar Soeharto mundur dijawab dengan tindakan militer menduduki kampus-kampus ITB dan UI, selain para pimpinan mahasiswa ditangkap dan kemudian diadili. Lebih jauh lagi, pemerintah juga membekukan DM (Dewan Mahasiswa)/SM (Senat Mahasiswa) se-Indonesia. Sejumlah surat kabar dibreidel, dan setelahnya keluarlah kebijakan NKK/BKK. Ada resistensi terhadap kebijakan ini, misalnya para aktivis mahasiswa ITB yang sempat berusaha mempertahankan DM lewat pelaksanaan pemilihan ketua DM secara langsung pada tahun 1981, tetapi akibatnya mereka menerima tindakan pemecatan dari pihak rektorat. Lihat Suryadi A. Radjab, “Budaya Tandingan Gerakan 5 Agustus”, prolog buku Enin Supriyanto. Menolak Tunduk: Menentang Budaya Represif. Jakarta: Grasindo, 1999, hal. ix-xxviii
[5] Lihat ibid.
[6] “Mereka Bicara Tentang PRD”, dalam Mingguan Sinar, 10 Agustus 1996
[7] FX Rudi Gunawan, Budiman Sudjatmiko Menolak Tunduk. Jakarta: Grasindo, 1999