Oleh: Nurani Soyomukti
Lebih buruk lagi ketika kita melihat fakta bahwa kisah cinta dijalani dan dipilih hanya karena ikut-ikutan. Maka aturan dan cara menjalaninya juga ikut-ikutan. Pada hal seharusnya tindakan cinta itu memerlukan pemikiran dan pengetahuan yang mendalam. Karena cinta bukanlah suatu hal yang abstrak, maka harus dikenali bagaimanakah ukuranm-ukurannya dan prakteknya yang membuat ia menguatkan hubungan—hubungan yang
 dibangun dengan baik, dan bukan diikuti secara mengalir begitu saja.
dibangun dengan baik, dan bukan diikuti secara mengalir begitu saja. Jika ukurannya adalah aliran perasaan, tentu saja akan banyak godaan-godaan dalam membangun hubungan. Dalam hubungan cinta eksklusif seperti pacaran dan pernikahan, jika masing-masing pihak yang berhubungan menjalaninya secara mengalir, maka tak akan diketahui arah dan tujuan hubungan itu. Bahkan kenapa mereka berhubungan dan bersatu juga tidak diketahui.
Ketidaktahuan tentang cinta, hubungan, dan kekasih kita akan melahirkan alienasi (keterasingan). Kebodohan adalah musuh umat manusia sepanjang abad, tepatnya musuh diri yang paling hakiki sebagai manusia yang konon telah lepas dari status kebinatangannya. Binatang itu tidak punya akal, pengembaraannya diatur oleh nafsu. Hewan adalah budak keinginan yang caranya hidup juga hanya untuk memenuhi keinginan itu sebagai “tuan” yang membuatnya tidak berpikir dalam bergerak.
Singkatnya, hubungan cinta yang maju lahir dari orang-orang yang menyatukan diri dan diikat dengan tujuan. Tidak capaian yang bisa diperoleh dari jiwa orang yang hidupnya absurd dan tak tahu untuk apa tujuan hidupnya dan tujuan hubungannya, tujuan cintanya. Biasanya ia terombang-ambing oleh lingkungan dan berbagai serangan-serangan pemikiran dan cara pandang dari luar dirinya, tetapi tetap saja ia tak dapat menyerap berbagai hal yang datang untuk mengisi pikiran dan hatinya. Ia tak punya patokan, tak punya ukura yang digunakan untuk menilai diri dan lingkungannya. Lalu, iapun berkata: “Hidupku mengalir, aku tak perlu patokan-patokan, aku tak perlu
 menetapkan nilai untuk segala sesuatu. Bahkan aku tak ingin menilai, pada karena aku tak mau menghakimi. Yang penting kepuasan kudapatkan dari semua ini”.
menetapkan nilai untuk segala sesuatu. Bahkan aku tak ingin menilai, pada karena aku tak mau menghakimi. Yang penting kepuasan kudapatkan dari semua ini”. Tetapi tampaknya pengetahuan juga menjadi naluri yang umum di setiap manusia. Aktifitas cuek tanpa pengetahuan dalam suatu hubungan akan membahayakan dan tampaknya merupakan hal yang jarang terjadi. Untuk membangun hubungan dengan seseorang yang ingin kita cintai, misalnya, aktifitas memahami dan memaknai kehadiran seseorang itu sangatlah niscaya. Seorang yang kemudian menjadi kekasih atau teman intim kita tentu adalah orang yang istimewa bagi kita—kecuali, sekali lagi, orang baru itu adalah perempuan yang dijumpai laki-laki di rumah bordir. Orang yang istimewa bagi kita awalnya adalah orang yang pada ’pandangan pertama’ menarik hati kita, setelah dekat ia menimbulkan pertanyaan: ”Siapakah ia?” Kitapun penasaran ingin mengetahui tentangnya.
Saat ada kesempatan bahwa kita semakin dekat dengannya, kita semakin penasaran dan banyak bertanya dan mencari tahu tentang dirinya. Jika ia memiliki pengetahuan dan pengalaman atau kelebihan yang tidak kita punyai, kita beranggapan bahwa orang inilah yang dapat melengkapi kita. Kita ingin menyatu dengan orang ini agar diri kita seakan menjadi lengkap. Kita ingin menjalin hubungan yang lebih erat dengan orang ini, kita ingin terus bersama, kita membangun komitmen—dan kemudian, misalnya, mengikatnya dengan pernikahan.
Sebagai bentuk hubungan eksklusif (sempit) dibanding hubungan antara sesama manusia yang lebih luas (universal), pernikahan merupakan model hubungan di mana sepasang manusia diasumsikan ingin melembagakan suatu bangunan relasi yang didasarkan pada tujuan yang lebih bersifat serius dan jangka panjang. Jadi di sini Nurani menegaskan adalah tujuan adalah kata kunci dan dari tujuan itulah kita bisa mengukur secara dini bagaimana suatu hubungan maju atau tidak.
Jika tujuan pernikahan adalah remeh, maka kita harus mengutuknya, mencegahnya dan jangan menirunya jika kita masih percaya pada cinta dan keadilan. Tak jarang orang-orang oportunis mencari perlindungan dan mengharapankan pamrih dari pernikahan. Dalam buku ”Intimacy”, saya menunjukkan beberapa hal yang dapat saya deteksi dari orang-orang yang melakukan pernikahan sebagai kedok dan untuk alasan kepentingan sempit dan oportunis barangkali adalah sebagai berikut: [1] pertama, untuk mendapatkan seks an sich. Yang masuk dalam kategori ini biasanya adalah orang yang hanya ingin segera bisa menikmati kenikmatan seksual dan tujuannya
 menikah hanyalah itu—biasanya yang lain-lainnya tak terlalu dipikirkan, tak dipersiapkan, dan dorongan yang mendesak dari melakukan pernikahan hanyalah seks; Ini biasanya berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan.
menikah hanyalah itu—biasanya yang lain-lainnya tak terlalu dipikirkan, tak dipersiapkan, dan dorongan yang mendesak dari melakukan pernikahan hanyalah seks; Ini biasanya berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kedua, menikah untuk mendapatkan fasilitas material saja. Tak jarang orang (biasanya lebih banyak perempuan) yang (baik terpaksa atau tidak) menikah agar segera mendapatkan orang yang dapat menghidupinya pada saat ia memang hanya akan tergantung pada orang lain. Terutama bagi perempuan yang tak produktif (menghasilkan pendapatannya sendiri) atau tak kerja, kondisi ketergantungannya akan sangat parah. Bagi perempuan yang memperoleh pendapatan pun, yang sering disebut ”perempuan independen”, mereka juga mengharapkan mendapatkan suami yang lebih kaya. Seakan kebanyakan perempuan memang lebih bahagia apabila ia mendapatkan suami yang lebih dan sangat kaya—seakan sudah menjadi naluri perempuan (meskipun tesis ini masih bisa diperdebatkan, karena ta mungkin suatu mental tak disebabkan oleh kondisi dan situasi historis).
Ketiga, tujuannya menunjukkan dominasi hubungan. Kebanyakan adalah laki-lakilah yang menganggap menikah sebagai alat agar ia mendapatkan pendamping (istri) yang bisa melayaninya, yang tunduk patuh padanya, yang mau memberinya keturunan tetapi untuk kejayaan dirinya sendiri—entah untuk menunjukkan eksistensi kelaki-lakiannya (keperkasaannya), dll. Keperkasaan dan narsisme semacam itu tak jarang ditunjukkan dengan ketidakberdayaan perempuan (istri) pada saat ia selingkuh baik resmi (poligami) maupun secara sembunyi-sembunyi.
Pertemuan antara perempuan yang tak produktif—saya menyebutnya sebagai ”parasite eves”—dengan laki-laki kaya yang cenderung narsis dan dominatif ini biasanya akan membuahkan penindasan dalam rumah tangga. Masalahnya: (1) si perempuan tak memiliki daya tawar ekonomis; dia tak memperoleh pendapatan sendiri dan hanya menggantungkan pada laki-laki (suam
 i); (2) sang suami merasa bahwa dialah sumber dari pendapatan, artinya sumber kekuasaan. Dalam pola pikir rasional yang kapitalistik, sang istri dianggap sebagai buruh yang diupah oleh majikan (suami) dengan tugas-tugas domestik, misalnya: melayani kebutuhan seksual suami, merawat anak-anak, memasakkan nasi, kadang juga mencucikan baju, membersihkan rumah, dan lain-lain.
i); (2) sang suami merasa bahwa dialah sumber dari pendapatan, artinya sumber kekuasaan. Dalam pola pikir rasional yang kapitalistik, sang istri dianggap sebagai buruh yang diupah oleh majikan (suami) dengan tugas-tugas domestik, misalnya: melayani kebutuhan seksual suami, merawat anak-anak, memasakkan nasi, kadang juga mencucikan baju, membersihkan rumah, dan lain-lain. Bentuk dekadensi semacam itulah yang membuat hubungan menjadi bentuk yang merusah kemanusiaan, yang kalau kita selidiki lebih lanjut akan membuahkan berbagai bentuk dehumanisasi yang lebih luas yang diterima karena terwariskan kepada anak-anak kita.[]
----------------------------------------------
[1] Nurani Soyomukti. Intimacy: Membangun Kebersamaan dalam Pacaran, Pernikahan, dan Merawat Anak dengan Surga Keintiman. Surabaya: Prestasi Pustaka, 2008.
*****************************************
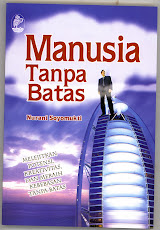





Tidak ada komentar:
Posting Komentar